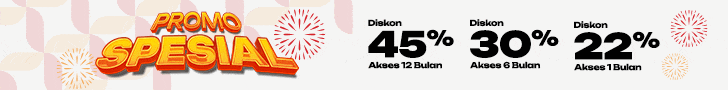Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
Ketika Duka, Penderitaan dan Keputusasaan Menjadi Bisikan Terakhir
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Seorang mahasiswi berusia 18 tahun ditemukan menangis sepanjang wawancara. Ia mengaku merasa sedih, pusing, lemas, sesak, dan tidak berdaya setiap kali mendengar suara sirene, yang mengingatkannya pada ibunya yang meninggal tiga bulan lalu akibat meningitis.
Sejak Juni ia sering memikirkan ibunya, dan keluhan ini memberat sejak satu bulan terakhir. Mahasiswi ini tinggal sendiri di Denpasar untuk kuliah dan merasa kesepian, tidak bisa mandiri, serta sangat bergantung pada orang tuanya, terutama ibunya.
Dalam satu bulan terakhir, ia mengalami kehilangan semangat hidup, pandangan suram terhadap masa depan, sering mengurung diri di kamar, gangguan pola makan (makan hanya sekali sehari), dan minat berkurang terhadap aktivitas yang sebelumnya disukai, seperti mendengarkan musik.
Ia juga mengalami gangguan tidur berupa sering terbangun di malam hari. Riwayat percobaan bunuh diri pernah ada pada bulan Agustus lalu dengan cara menelan lebih dari lima tablet parasetamol dan menyayat pergelangan tangan kirinya, yang dilakukannya untuk merasa lega. Saat ini ia melaporkan adanya perasaan berat di kepala serta suara yang menyuruhnya menyerah dan mengakhiri hidupnya.
Sebelum ibunya meninggal, ia digambarkan sebagai pribadi yang aktif dalam kepanitiaan dan kehidupan sosial tanpa gangguan akademik. Pada saat orientasi kampus, ia mendadak jatuh, lemas, dan tidak merespon ajakan bicara, dengan pandangan kosong. Sehari sebelumnya ia sudah mengeluhkan pusing dan tidak enak badan.
Menurut kakaknya, sejak kematian ibunya adik ini sering mengunggah postingan tentang sang ibu di media sosial. Namun keluarga tidak mengetahui aktivitasnya selama kuliah karena ia jarang bercerita dan tinggal sendiri. Kakaknya juga tidak mengetahui riwayat perilaku membahayakan diri atau tanda-tanda aneh saat berkomunikasi. Apa sebenarnya yang terjadi pada mahasiswi ini? Kenapa sebuah kehilangan dapat memunculkan keinginan untuk bunuh diri?
Gambaran klinis dan diagnosis awal
Kasus mahasiswi berusia 18 tahun ini mempresentasikan gambaran klinis yang sangat mengkhawatirkan sebagai bagian dari suatu kondisi yang melampaui duka biasa. Seiring kematian ibunya tiga bulan lalu akibat meningitis, muncul serangkaian gejala emosional dan keluhan fisik yaitu kesedihan mendalam, kehilangan minat (anhedonia), gangguan tidur (sering terbangun), pola makan menurun (makan sekali sehari), energi yang sangat rendah, dan pandangan suram terhadap masa depan. Yang paling mengkhawatirkan ialah adanya ide bunuh diri dan riwayat percobaan bunuh diri (parasetamol >5 tablet, penyayatan tangan).
Menurut kriteria diagnosis International Classification of Diseases (ICD-11), gambaran seperti ini kuat mengarah ke diagnosis gangguan depresi berat dengan gejala psikotik dan ide bunuh diri, dengan kemungkinan komorbid gangguan kecemasan atau stres.
Beberapa faktor yang mendukung diagnosis ini, adanya durasi gejala (lebih dari 2 minggu), gangguan fungsi (menyendiri, kurang aktivitas, penurunan kemampuan menjaga diri sendiri), serta adanya risiko bunuh diri yang nyata. Meskipun gangguan penyesuaian bisa muncul pasca stresor kehilangan yang besar, karakter intensitas gejala dan ide bunuh diri menjadikan gangguan penyesuaian saja kurang memadai.
Namun, diagnosis tidak boleh berhenti di situ karena gejala jatuh mendadak dan kehilangan kesadaran temporer (pandang kosong, tidak responsif) perlu dievaluasi pula secara medis. Ada kemungkinan sinkop, gangguan neurologis atau metabolik harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, pemeriksaan fisik lengkap, laboratorium umum, serta konsultasi neurologi dan psikiatri diperlukan.
Dalam ranah ilmu tentang bunuh diri modern, teori-teori kontemporer membantu menjelaskan mengapa pasien ini bisa terperangkap dalam siklus pikiran bunuh diri. Model Integrated Motivational-Volitional (IMV) menunjukkan bahwa fase motivasional (defeat, entrapment) memunculkan ide, dan faktor volisional (capability, impulsivitas, pengurangan sensasi takut akan kematian) yang memungkinkan adanya transisi ke tindakan bunuh diri.
Begitu pula Three-Step Theory (3ST) mengemukakan bahwa ide muncul ketika rasa sakit psikologis ditambah dengan hopelessness hadir, lalu kebutuhan keterhubungan yang rendah dan seseorang memiliki kemampuan untuk bunuh diri akan memungkinkan terjadinya sebuah tindakan nyata. Dalam kasus ini, meskipun ibunya meninggal bukan karena bunuh diri, dampak kehilangan emosional yang intens dan kurangnya jaringan dukungan sosial memperparah kerentanan psikologis yang dialami.
Selain itu aspek regulasi emosi juga menjadi faktor risiko penting dimana kesulitan dalam mengatur afek, ledakan emosi yang mencekam, atau pengalaman psikis (rasa sakit mental tak tertahankan) sering dikaitkan dengan munculnya ide bunuh diri.
Sehingga dalam kasus ini, faktor-faktor seperti kesepian, perasaan kehilangan dan beban emosional, pengalaman psikologis yang menyakitkan karena duka mendalam, serta kemampuan dan pengalaman menyakiti diri (melalui penyayatan) berpotensi menjadi rangkaian proses suicidogenik. Perlu dipahami bahwa setelah satu episode depresi berat, risiko mengalami episode berikutnya meningkat hingga 50–60% dalam 2 tahun ke depan bila tidak mendapat pengobatan yang tepat.
Psikodinamika, kehilangan, dan evolusi keinginan bunuh diri
Untuk memahami bagaimana keputusasaan seseorang berkembang menjadi keinginan bunuh diri, kita perlu melihat interaksi antara dinamika psikodinamik tradisional dan teori psikologis modern secara utuh. Dalam sudut pandang psikodinamika klasik, kematian orang yang sangat dicintai memicu proses mourning, namun pada individu yang rentan, proses ini dapat berubah menjadi melankolia yaitu kehilangan eksternal berubah menjadi konflik internal.
Ego menjadi sasaran kritik diri, dan objek yang hilang diinternalisasi sebagai objek ego yang rusak. Dalam kasus ini, sosok ibu merupakan figur pengasuh dan penopang identitas emosional yang sangat kuat, sehingga kehilangan mendadak mengganggu stabilitas ego dan struktur mentalnya.
Ada kemungkinan terdapat ambivalensi tersembunyi (cinta sekaligus kemarahan atau rasa bersalah) yang belum disadari dan kemudian diproyeksikan menjadi kritik diri yang ekstrem atau dorongan destruktif terhadap diri sendiri. Superego yang keras menghakimi dirinya karena dianggap tidak cukup kuat dapat memunculkan agresi internal sehingga keinginan bunuh diri sebagai jalan keluar dari penderitaan batin yang berat.
Teori modern seperti Integrated Motivational-Volitional Model (IMV) menjelaskan bahwa ide bunuh diri timbul dari perasaan kalah, terjebak, dan rendahnya keterhubungan sosial atau perasaan menjadi beban. Dalam kasus ini, mahasiswi ini merasa kesepian di Denpasar dan kehilangan figur ibu yang menjadi sumber keterhubungan emosionalnya, sehingga keterhubungan sosial menyusut dan muncul beban emosional terhadap keluarga.
Pada fase tindakan, individu yang telah memiliki pengalaman menyakiti diri, misalnya penyayatan tangan atau percobaan bunuh diri akan memiliki kemampuan untuk bunuh diri yang lebih tinggi. Dorongan ini diperkuat oleh impulsivitas atau keletihan mental yang akut serta menurunnya ketakutan terhadap kematian. Pemicu eksternal, seperti suara sirene yang menimbulkan gejala fisik kecemasan, dapat bertindak sebagai pemicu yang mempercepat tindakan bunuh diri.
Model Three-Step Theory juga mendukung pemahaman ini, di mana penderitaan psikologis dan keputusasaan akan menghasilkan ide, lalu rendahnya keterhubungan sosial dan tingginya toleransi terhadap rasa sakit memfasilitasi transisi menuju tindakan nyata. Ide bunuh diri juga memiliki pola waxing and waning (muncul dan reda). Seseorang bisa tampak membaik lalu gejala kembali pada saat stresor baru, rasa kehilangan baru, atau pemicu emosional tertentu. Riwayat menyakiti diri meningkatkan risiko berulangnya percobaan bunuh diri di masa depan.
Dalam teori kedukaan modern, konsep continuing bonds menyatakan bahwa hubungan batin dengan orang yang telah meninggal tidak mesti dihapuskan, melainkan diubah bentuknya sehingga kenangan dan nilai yang diinternalisasi tetap menjadi bagian dari identitas penyintas.
Namun, jika hubungan tersebut tidak berhasil diintegrasikan secara sehat, misalnya diratapi secara terus menerus atau dijadikan tolok ukur ideal yang tak terjangkau, maka ia dapat menjadi beban emosional yang memperkuat ide bunuh diri. Dalam kasus ini, ia sering memikirkan ibunya sejak Juni, mengunggah postingan tentang beliau, dan terus membawa bayangannya dalam kesunyian kamar.
Seiring waktu, hubungan internal tersebut mungkin berubah dari hubungan penuh kasih menjadi sumber konflik batin yang memunculkan rasa bersalah, ketidakmampuan, dan keputusasaan.
Transisi dari duka menjadi destruksi tidak bersifat mekanis. Dalam proses ini, ia membangun kembali objek internal yang rusak, melunakkan kritik superego, dan mengonstruksi ulang narasi identitas yang lebih berbelas kasih terhadap diri sendiri.
Narasi baru memungkinkan ia tetap menjaga ikatan dengan ibunya sebagai bagian dari identitas masa depan tanpa terus menjadi tahanan beban emosional. Ia akan bergerak antara fase menerima kehilangan dan fase memperbaiki kehidupannya kembali sesuai dual process model of coping, di mana fluktuasi antara orientasi kerugian dan orientasi pemulihan merupakan bagian dari duka yang adaptif.
Dengan demikian, evolusi keinginan bunuh diri dapat dianggap sebagai titik ekstrem di mana konflik internal, kegagalan regulasi emosi, keterasingan sosial, dan pengalaman menyakiti diri bersama-sama menciptakan tekanan psikologis yang tampak tak tertahankan. Jika proses berduka tidak berjalan adaptif, ia bisa menjadi complicated grief atau persistent complex bereavement disorder. Kondisi ini cenderung menetap atau muncul kembali secara episodik pada saat-saat pemicu emosional (anniversary, tempat tertentu, suara tertentu seperti sirine).
Resiliensi dan rekonsiliasi
Untuk mencegah tragedi yang lebih dalam, dibutuhkan strategi intervensi yang bersifat menyeluruh, tidak hanya menyasar individu, tetapi juga lingkungan sosial dan sistem pelayanan kesehatan mental yang menopang. Pada tingkat individu, langkah pertama adalah membangun kembali daya tahan dan harapan melalui terapi yang secara khusus menargetkan ide bunuh diri.
Selain itu, penting pula menyusun safety planning dan crisis response planning secara kolaboratif antara terapis dan pasien. Rencana ini berisi langkah-langkah konkret ketika ide bunuh diri muncul, seperti menelepon orang yang dipercaya, melakukan teknik distraksi, atau memastikan tidak ada akses terhadap alat bunuh diri sehingga pasien memiliki pegangan saat menghadapi dorongan impulsif.
Pemulihan juga membutuhkan penguatan hubungan sosial dan dukungan interpersonal. Ia perlu kembali terhubung dengan keluarga, bahkan bila jarak memisahkan, melalui telekonseling atau video call agar tetap merasakan kehadiran emosional orang terdekat. Keterlibatan dalam kelompok peer-support, baik kelompok duka, komunitas mahasiswa, maupun organisasi sosial diyakini mampu menumbuhkan rasa kebersamaan yang selama ini hilang.
Dukungan dari teman sebaya yang terlatih menjadi krusial, terutama pada masa transisi seperti saat kembali ke kos atau menghadapi malam-malam rawan kesepian. Semua bentuk keterhubungan ini bukan sekadar masalah sosial, tetapi juga bersifat terapeutik, karena mengembalikan fungsi dasar manusia untuk merasa diakui dan didengar.
Langkah berikutnya adalah rekonstruksi makna dan naratif kehidupan. Melalui proses ini, kehilangan tidak lagi menjadi sumber penderitaan permanen, melainkan fondasi bagi pematangan diri. Eksperimen simbolik seperti menulis surat kepada almarhum ibu, membuat ritual kenangan, atau berkegiatan sosial atas nama nilai-nilai yang diwariskan dapat menjadi media rekonsiliasi emosional yang menyehatkan.
Tahapan terakhir di tingkat individu adalah pemeliharaan jangka panjang dan pemantauan berkesinambungan. Setelah krisis mereda, fase ini sangat penting untuk mencegah kekambuhan. Follow-up intensif dilakukan untuk mendeteksi munculnya kembali ide bunuh diri, memastikan kepatuhan terhadap rencana keamanan, serta menjaga kontinuitas hubungan terapeutik.
Namun, intervensi individual tidak akan berhasil tanpa dukungan lingkungan yang kondusif. Masyarakat dan lingkungan kampus memegang peranan penting dalam membangun ekosistem pencegahan dan pemulihan. Kampanye literasi kesehatan mental di kampus menjadi langkah awal yang vital.
Pendidikan tentang kesehatan emosional, proses berduka, dan strategi coping harus menjadi bagian dari kurikulum atau kegiatan kemahasiswaan. Pelatihan gatekeeper bagi dosen, staf kemahasiswaan, dan mahasiswa berpengaruh perlu digalakkan agar mereka mampu mengenali tanda bahaya dan segera merujuk ke tenaga profesional.
Layanan konseling kampus, hotline krisis, dan ruang aman yang dapat diakses secara anonim juga perlu tersedia agar mahasiswa tidak merasa sendirian menghadapi krisis psikologis.
Selain itu, pengurangan stigma terhadap depresi, duka, dan ideasi bunuh diri harus menjadi prioritas. Kampanye publik harus menekankan bahwa gangguan kesehatan mental bukan aib, melainkan kondisi yang dapat ditangani dengan bantuan dan empati. Forum terbuka dan kelompok dukungan duka memungkinkan individu untuk berbagi pengalaman tanpa rasa takut dihakimi.
Kampus juga perlu mengadopsi kebijakan yang ramah kesehatan mental, seperti izin akademik khusus, cuti pemulihan, dan fleksibilitas jadwal bagi mahasiswa dengan gangguan emosional berat. Dukungan kelembagaan seperti ini menunjukkan bahwa sistem benar-benar berpihak pada penyintas, bukan menambah beban mereka.
Langkah lain yang tidak kalah penting adalah kontrol terhadap akses cara bunuh diri. Kampus dan lingkungan tempat tinggal mahasiswa dapat memperketat pengawasan terhadap obat-obatan dosis tinggi, terutama yang dijual bebas seperti parasetamol. Edukasi mengenai keamanan obat dan bahaya overdosis harus diberikan secara terbuka.
Pengawasan terhadap fasilitas fisik seperti kamar kos juga penting untuk memastikan tidak ada sarana yang dapat digunakan untuk mencederai diri tanpa terdeteksi. Upaya-upaya ini tidak bertujuan membatasi kebebasan, melainkan menciptakan lingkungan yang aman dari tindakan impulsif yang berpotensi fatal.
Kolaborasi lintas sektor juga harus diperkuat. Layanan kesehatan mental perlu diintegrasikan dengan klinik kampus atau fasilitas kesehatan primer agar mahasiswa dapat disaring secara dini. Dalam menghadapi kasus seperti ini, kita dihadapkan pada tantangan besar, bagaimana membangun pagar keamanan sebelum penderitaan menjelma menjadi tragedi.
Kesedihan mendalam akibat kehilangan ibu tidak bisa dianggap sebagai duka biasa yang akan sembuh dengan waktu, terlebih ketika sudah menunjukkan sisi destruktif berupa ide dan percobaan bunuh diri. Tanggung jawab tidak berhenti di tangan profesional kesehatan mental namun pihak kampus, keluarga, teman sebaya, dan komunitas harus bersama-sama membentuk jejaring dukungan yang hangat dan responsif.
Oleh karena itu, setiap lapisan masyarakat perlu mengambil peran aktif dalam mencegah dan menyembuhkan karena setiap kehidupan yang terselamatkan bukan sekadar angka, melainkan harapan yang kembali tumbuh di tengah kesunyian. (Oleh: Prof Dr dr Cokorda Bagus Jaya Lesmana, SpKJ(K), MARS)
Editor: Redaksi
Reporter: bbn/tim
Berita Terpopuler
Pedagang Pasar Kumbasari Cemas Tukad Badung Meluap Lagi
Dibaca: 131 Kali
Halloween di Bandara Ngurah Rai Usung Mitologi Bali
Dibaca: 94 Kali
1.000 Personel Amankan Kejuaraan Dunia Vovinam di Buleleng
Dibaca: 83 Kali
Korban Hanyut di Ubud Ditemukan Tewas di Sukawati
Dibaca: 46 Kali
ABOUT BALI

Film Dokumenter Hidupkan Kembali Sejarah Tari Kecak di Bedulu

Makna Tumpek Landep Menurut Lontar Sundarigama

Tari Sanghyang Dedari Nusa Penida Diajukan Jadi Warisan Budaya Tak Benda

Mengenal Tetebasan Gering, Topik Menarik di Festival Lontar Karangasem