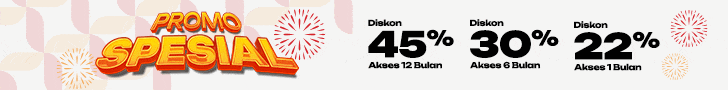Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
Gema Suara Ayah Membawa Luka yang Tidak Terselesaikan
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Seorang laki-laki berinisal KDS, pelajar berusia 18 tahun, dikeluhkan oleh ibunya sering marah-marah sejak satu tahun terakhir setelah ayahnya meninggal, dengan perburukan empat hari sebelum masuk rumah sakit.
Kemarahan memuncak setelah mengetahui ibunya memiliki pacar baru yang tidak ia sukai dan ia curigai tidak dapat membahagiakan ibunya. Ia merasa semakin kesal, marah, dan curiga saat mendengar suara gonggongan anjing, suara cicak, dan orang-orang berbincang ribut di sekitarnya, serta mengeluhkan tangan gemetar sejak dirawat.
Ia sering memikirkan ayahnya dan merasa bersalah karena dahulu tidak patuh. Ia sering mengingat perkataan ayahnya yaitu “Nanti kalau Bapak sudah tidak ada baru kamu rajin, baru kamu tau, baru kamu paham,” perkataan ini menggema di kepalanya secara terus menerus, tidak dapat dihentikan dan dikontrol.
Pikiran ini terus mengganggu hingga kehilangan fokus dan sulit beristirahat. Sejak ayahnya meninggal, ia menjadi sedih terus-menerus, sering mengunjungi tempat kejadian, jarang keluar rumah, dan kehilangan minat bergaul dengan teman. Ia pernah memiliki pikiran untuk bunuh diri namun takut untuk melakukannya.
Beberapa minggu sebelum dirawat, ia melihat bayangan dan suara ayahnya yang berbisik di kedua telinga menyemangatinya untuk sekolah. Ia mengatakan sulit untuk mempertahankan tidur dan sering terbangun hingga pernah tidak tidur sama sekali selama empat hari.
Ia merasa tetap segar dan berenergi walaupun tidak tidur. Ia mengatakan pernah ada keinginan untuk mengamuk tanpa alasan secara tiba-tiba. Ia menyadari bahwa dirinya sakit dan tidak dapat mengontrol emosinya, namun bingung mengapa dirinya menjadi seperti ini.
Remaja, duka, dan pikiran untuk mengakhiri Hidup
Usia 18 tahun seharusnya menjadi masa yang penuh warna dan waktu ketika seorang anak muda mulai merasakan cita, cinta, dan makna hidup di luar rumah. Namun, bagi KDS, remaja laki-laki berusia 18 tahun, masa ini berubah menjadi ruang hening yang penuh kemarahan, kesedihan, dan perasaan bersalah.
Sejak ayahnya meninggal, dunia yang ia kenal seakan runtuh. Ia menjadi mudah marah, curiga, bahkan mulai mendengar suara dan bayangan ayahnya. Di tengah itu semua, pernah terlintas dalam pikirannya untuk mengakhiri hidup.
Mengapa seorang remaja yang seharusnya menikmati masa muda justru berpikir tentang kematian? Pertanyaan ini menjadi penting bukan hanya bagi para profesional kesehatan jiwa, tetapi juga bagi orang tua, guru, dan masyarakat yang menyaksikan semakin banyak anak muda kehilangan semangat hidup.
Kematian orang tua di usia remaja merupakan salah satu peristiwa paling traumatis dalam kehidupan manusia dan meningkatkan risiko depresi, gangguan stres pasca-trauma, serta ide bunuh diri secara signifikan. Duka pada usia ini belum bisa diolah dengan kedewasaan emosional penuh. Ketika dukacita tidak diberi ruang untuk diekspresikan, ia berubah menjadi marah, curiga, bahkan gejala psikotik ringan.
Bagi KDS, kepergian ayahnya bukan hanya kehilangan figur, tetapi juga kehilangan arah. Kalimat terakhir sang ayah, “Nanti kalau Bapak sudah tidak ada, baru kamu tahu” menjadi gema batin yang tidak pernah padam. Dalam dunia psikodinamik, ini disebut introyeksi yaitu internalisasi figur orang tua yang meninggalkan bekas kuat dalam alam bawah sadar. Ketika rasa bersalah dan duka bercampur, remaja bisa merasa bahwa satu-satunya cara menenangkan suara di kepala adalah dengan mengakhiri segalanya.
Beberapa bulan setelah kepergian ayah, sang ibu mulai dekat dengan seseorang yang baru. Secara sosial mungkin wajar, tetapi bagi remaja yang masih berduka, hal itu bisa terasa seperti pengkhianatan. Ia merasa tidak siap melihat ibunya dicintai orang lain. Ini mengguncang identitasnya sebagai pelindung ibu dan pewaris cinta ayah. Konflik keluarga pascakehilangan adalah pemicu kuat munculnya ide bunuh diri pada remaja, terutama bila tidak disertai komunikasi terbuka.
Selama berminggu-minggu, KDS mengalami kesulitan tidur bahkan pernah tidak tidur selama empat hari. Ia merasa tetap segar, penuh tenaga, dan mudah marah. Dalam psikiatri modern, gangguan tidur ekstrem adalah tanda bahaya utama. Tidur kurang dari 6 jam per malam meningkatkan risiko depresi dan percobaan bunuh diri hingga dua kali lipat. Kurang tidur bukan sekadar lelah fisik namun juga merusak regulasi emosi dan mengubah cara otak memproses stres.
Dalam budaya pada umumnya, duka sering dibingkai dengan konsep spiritual. Namun di balik ritual itu, sering kali remaja tidak diajak bicara tentang makna kehilangan. KDS mungkin diminta untuk tabah, padahal ia butuh ruang untuk menangis, bertanya, dan merasa marah. Tanpa ruang ekspresi emosional, duka menjadi beku. Ia tidak hilang, tetapi membusuk dalam diam dan muncul kembali dalam bentuk kemarahan, curiga, dan rasa bersalah.
Memahami interaksi kompleks antara jiwa, lingkungan, dan otak
Untuk memahami perilaku dan pikiran KDS, kita tidak cukup melihat dari satu sisi. Dalam pandangan psikodinamik, setiap individu membawa objek internal dimana figur signifikan yang membentuk cara kita mencintai, marah, dan merasa bersalah. KDS masih hidup bersama ayahnya di dunia batin.
Ucapan ayah yang menggema seperti kaset rusak adalah simbol konflik batin yang belum terselesaikan bagaikan cinta yang bercampur rasa bersalah. Suara ayah yang ia dengar mungkin bukan gejala skizofrenia, melainkan ekspresi mourning psychosis, di mana pikiran tak sadar memunculkan suara sebagai bentuk mempertahankan hubungan dengan yang hilang.
Kemarahan KDS terhadap ibunya sebenarnya bukan sekadar kemarahan biasa. Ia adalah manifestasi dari duka yang belum terselesaikan, kehilangan yang tak bisa dipahami, dan cinta yang kehilangan arah. Sejak ayahnya meninggal, KDS memendam perasaan bersalah yang dalam karena merasa tidak sempat menjadi anak yang patuh dan membanggakan. Dalam pikirannya, suara ayah masih hidup dan berulang kali mengingatkannya akan kata-kata terakhir sebelum wafat. Suara itu menjadi gema batin yang menekan dan menghantui, membuatnya sulit membedakan antara penyesalan dan kenyataan.
Di tengah perasaan bersalah itu, ia menyaksikan ibunya mencoba melanjutkan hidup dengan seseorang yang baru. Bagi KDS, peristiwa ini seperti pukulan kedua setelah kehilangan pertama yaitu kehilangan figur ayah yang ia cintai, lalu kehilangan figur ibu yang kini dirasa menjauh.
Secara psikologis, kemarahan adalah bagian dari proses berduka. Namun, pada KDS, duka itu tidak pernah mendapat ruang aman untuk disampaikan. Ia menekan kesedihannya, menahan tangisnya, dan menggantinya dengan amarah karena bagi seorang remaja laki-laki, marah lebih mudah diterima daripada menangis.
Dalam batinnya, KDS tidak benar-benar marah pada ibunya sebagai pribadi, tetapi pada kenyataan bahwa dunia yang ia kenal sudah berubah. Ia merasa seolah ibunya melupakan ayahnya terlalu cepat, seolah cinta yang dulu menyatukan mereka kini bisa digantikan oleh orang lain. Di sisi lain, ia juga marah pada dirinya sendiri karena tidak mampu melindungi ibunya dan tidak sanggup memenuhi amanat ayahnya. Dalam psikodinamik, kondisi ini disebut ambivalence of attachment di mana cinta dan benci hadir bersamaan terhadap figur yang sama.
Secara relasional, perubahan dalam struktur keluarga setelah kematian ayah membuat KDS kehilangan posisinya. Ia mungkin merasa bertanggung jawab untuk menjaga ibunya, menggantikan peran ayah, atau menjadi laki-laki satu-satunya di rumah. Ketika ibunya mulai dekat dengan seseorang, tanggung jawab dan peran itu mendadak tidak lagi relevan. Ia merasa tidak dibutuhkan, tersisih, bahkan tergantikan.
Ini bukan sekadar rasa cemburu, tetapi perasaan kehilangan identitas dalam sistem keluarga. Rasa tidak berdaya itu berubah menjadi kemarahan karena ia tidak tahu bagaimana mengartikulasikan kehilangan tersebut. Dalam diam, KDS sebenarnya sedang berkata, “Aku takut kehilangan Ibu juga, seperti aku kehilangan Ayah.”
Dari sisi sosial, KDS terputus dari jejaring dukungan. Ia jarang keluar rumah, kehilangan teman, dan hidup dalam ruang sunyi yang penuh kenangan. Sebuah isolasi sosial pascakehilangan meningkatkan risiko bunuh diri hingga 3,2 kali lipat. Remaja membutuhkan keterhubungan dengan sekolah dan teman sebaya untuk menumbuhkan harapan. Remaja laki-laki diharapkan kuat, rasional, tidak cengeng. Norma ini membuat banyak remaja menekan kesedihan hingga berubah menjadi kemarahan. Marah seolah-olah menjadi satu-satunya emosi yang diizinkan. Padahal, kemarahan yang tidak dipahami adalah bentuk duka yang belum sempat menangis.
Secara biologis, remaja adalah periode ketidakseimbangan antara sistem emosi (amigdala) yang sudah matang dan sistem kontrol (prefrontal cortex) yang masih berkembang. Ini menjelaskan mengapa mereka impulsif dan sulit menenangkan diri. Dalam kasus KDS, stres berat, sulit tidur, dan rasa bersalah yang kronis menstimulasi sumbu hypothalamic–pituitary–adrenal axis (HPA axis) dan menyebabkan lonjakan hormon stres kortisol yang berkepanjangan.
Adanya disfungsi sirkuit fronto-limbik dan gangguan serotonin berperan dalam munculnya ide bunuh diri. Otak yang lelah karena stres tidak lagi mampu menilai risiko dan makna hidup secara jernih. Ketika dunia batin, sosial, dan biologis runtuh bersama, bunuh diri tampak seperti satu-satunya cara mengakhiri suara di kepala.
Upaya melindungi anak dari proses kehilangan
Kisah KDS bukan hanya kisah seorang remaja yang sakit. Ia adalah cermin dari ribuan anak muda yang kehilangan arah dalam kesunyian rumah, tekanan sekolah, dan dunia digital yang tak kenal jeda. Sebagai Guru Besar Psikiatri Komunitas dan Budaya, saya ingin mengajak kita semua, keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat melihat lebih dalam dan bertindak lebih manusiawi.
Keluarga adalah tempat pertama dan terakhir bagi jiwa untuk beristirahat. Ketika kehilangan datang, keluarga perlu menciptakan ruang duka yang sehat. Ajak anak bicara tentang rasa sakit, bukan hanya tentang kewajiban untuk ikhlas. Remaja seperti KDS tidak butuh nasihat panjang namun ia butuh didengar tanpa dihakimi.
Ia perlu tahu bahwa menangis bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk keberanian menghadapi kenyataan. Keluarga juga perlu peka terhadap tanda bahaya seperti gangguan tidur, isolasi sosial, kehilangan minat, suara yang tidak nyata, atau kalimat seperti aku ingin pergi. Jangan menunggu sampai krisis datang namun cari bantuan profesional segera.
Selain itu ruang sekolah dapat berperan juga dalam hal ini bukan hanya tempat belajar, tetapi juga tempat tumbuh. Guru dan konselor harus dilatih mengenali tanda depresi dan ideasi bunuh diri pada siswa. Program membangun rasa keterikatan siswa dengan lingkungan sekolah telah terbukti menurunkan risiko bunuh diri hingga 30%. Beri ruang bagi siswa untuk bicara, berkreasi, dan memproses duka melalui seni, olahraga, atau kegiatan sosial. Dan yang paling penting adalah jadilah teladan empati. Satu guru yang mau mendengar bisa menyelamatkan satu nyawa.
Sementara itu pemerintah juga harus menempatkan kesehatan jiwa remaja sebagai prioritas. Screening rutin di sekolah dan puskesmas perlu dilakukan untuk deteksi dini depresi dan risiko bunuh diri. Kematian orang tua harus diperlakukan sebagai faktor risiko serius dimana setiap anak yatim atau piatu memerlukan pendampingan psikososial, bukan sekadar bantuan ekonomi. Di tingkat nasional, kampanye literasi kesehatan jiwa harus membongkar stigma bahwa anak yang marah itu nakal atau anak sedih itu manja. Mereka sedang berjuang, bukan gagal.
Kita semua memiliki peran. Jangan biarkan anak-anak tumbuh di tengah kebisingan dunia tanpa tempat bernaung. Ciptakan lingkungan sosial yang ramah terhadap perasaan. Ketika melihat remaja menyendiri, jangan hanya berkata semangat ya, tapi tanyakan dengan tulus, “Apa yang kamu rasakan hari ini?” Bentuk komunitas kecil di banjar, di kampus, di kelompok olahraga atau tempat di mana anak muda bisa berbagi tanpa takut dihakimi. Peer-support berbasis komunitas menurunkan angka percobaan bunuh diri hingga 25%.
Belajar dari kasus ini, KDS sedang berada di persimpangan antara kehilangan dan pencarian makna. Ia bukan remaja nakal, melainkan seorang anak yang berduka terlalu dalam tanpa tahu cara mengeluarkannya. Bagi kita, kisah ini mengingatkan bahwa suara-suara dalam kepala seseorang bisa menjadi jeritan yang tak terdengar oleh dunia luar. Maka tugas kita bukan hanya mengobati, tetapi juga menyimak.
Mendengar dengan empati, menyentuh dengan kehangatan, dan menuntun mereka menemukan kembali makna hidup. Semoga setiap anak yang kehilangan, menemukan kembali dirinya di pelukan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang lebih berbelas kasih. (Oleh: Prof Dr dr Cokorda Bagus Jaya Lesmana, SpKJ(K), MARS)
Editor: Redaksi
Reporter: bbn/tim
Berita Terpopuler
6.532 Warga Turun ke Jalan, Tabanan Gelar Grebeg Sampah Serentak
Dibaca: 6309 Kali
Pelajar Tabanan Raih Prestasi Nasional FLS2N 2025, Bupati Sanjaya Bangga
Dibaca: 5160 Kali
Turis Somalia Ngamuk Tuduh Sopir Curi HP, Ternyata Terselip di Jok Mobil
Dibaca: 4602 Kali
Gudang BRI Ubud Ambruk Akibat Longsor
Dibaca: 4430 Kali
ABOUT BALI

Film Dokumenter Hidupkan Kembali Sejarah Tari Kecak di Bedulu

Makna Tumpek Landep Menurut Lontar Sundarigama

Tari Sanghyang Dedari Nusa Penida Diajukan Jadi Warisan Budaya Tak Benda

Mengenal Tetebasan Gering, Topik Menarik di Festival Lontar Karangasem