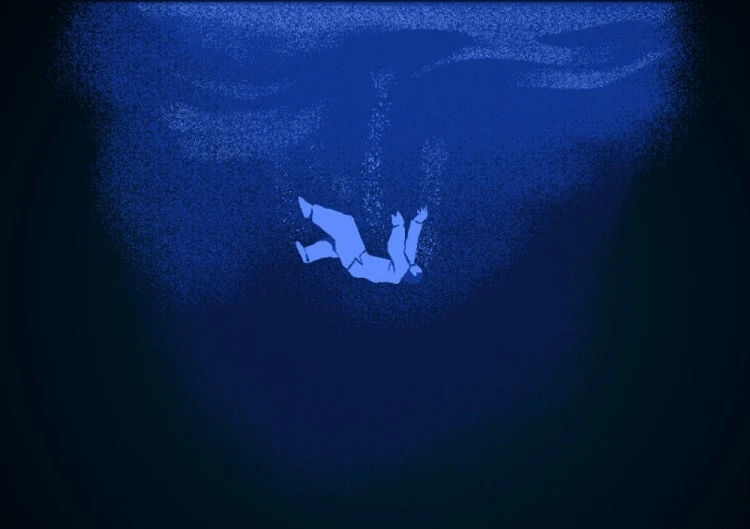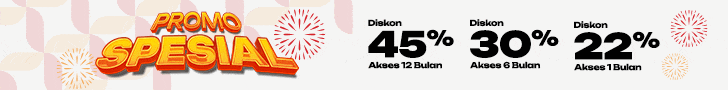Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
Pergi Tanpa Firasat, Sebuah Tragedi Meloncat dari Jembatan Dalam Sunyi
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Kasus bunuh diri dengan meloncat dari jembatan kembali terjadi di Bali. Diberitakan dari media, seorang pemuda berusia 26 tahun, ditemukan tewas setelah melompat dari Jembatan Tukad Bangkung, Petang, Badung, pada Kamis (25/9/2025).
Peristiwa tragis ini diduga sebagai tindakan bunuh diri, mengingat korban langsung terjatuh ke dasar jurang dan meninggal dunia di tempat. Jembatan Tukad Bangkung sendiri dikenal sebagai jembatan tertinggi di Bali.
Kabar duka ini mengejutkan keluarga besar korban. Ia dikenal sebagai sosok ramah, penuh canda, dan tidak pernah menimbulkan masalah. Sang ibu, mengaku sangat terpukul atas kepergian putranya. Ia menceritakan bahwa sehari sebelumnya, masih sempat bercanda dengan dirinya dan adiknya di rumah. Tidak ada tanda-tanda atau firasat yang mengarah pada niat bunuh diri. Bahkan, permintaan terakhir korban hanyalah agar sandalnya dicucikan.
Sehari-hari, ia bekerja di Pasar Kumbasari, Denpasar, sebagai pemungut iuran (cingkreman). Aktivitas terakhirnya pada Rabu (24/9) berlangsung normal, ia berangkat kerja pukul 15.00 WITA, pulang sekitar pukul 20.00 WITA, lalu sempat keluar lagi sekitar pukul 21.00 WITA.
Namun, pada dini hari sekitar pukul 01.00 WITA, ia kembali meninggalkan rumah tanpa diketahui tujuannya. Keesokan harinya, keluarga mendapat kabar duka dari aparat kepolisian dan kelian banjar.
Keluarga dan kerabat masih sulit menerima kenyataan ini. Mereka menegaskan bahwa korban tidak memiliki masalah dengan pasangan, keluarga, ataupun urusan pribadi lainnya. Para tetangga juga mengenangnya sebagai pemuda sopan yang selalu menyapa setiap orang.
Kepergiannya secara mendadak tidak hanya meninggalkan luka mendalam bagi orang tua dan lingkungan sekitarnya namun juga pertanyaan bagi kita semua kenapa kasus bunuh diri masih terus terjadi dan apa yang harus kita lakukan untuk dapat mencegah tidak terjadi kembali kasus serupa.
Luka yang tak terlihat
Secara psikologis, bunuh diri sering kali merupakan puncak dari proses panjang pergulatan batin yang kompleks. Tidak jarang individu yang sedang berada dalam tekanan emosional berat justru mampu menampilkan wajah yang tampak tenang, ramah, dan fungsional di hadapan keluarga atau lingkungan sekitarnya.
Fenomena ini dikenal dalam psikologi sebagai depresi terselubung, yaitu kondisi ketika seseorang tetap tampak ceria secara lahiriah tetapi menyimpan kesedihan atau tekanan batin yang mendalam. Dalam kasus pemuda ini, keluarga menegaskan bahwa korban tidak menunjukkan perilaku aneh atau menyimpan masalah besar.
Ia masih bercanda dengan ibu dan adiknya sehari sebelum kejadian, bahkan permintaan terakhirnya hanyalah agar sandalnya dicucikan. Sebuah hal sederhana yang sama sekali tidak memberi isyarat keputusasaan. Kondisi semacam ini menunjukkan adanya distress internal yang tersembunyi, di mana individu mungkin merasa tidak ingin merepotkan orang lain atau kesulitan menemukan kata untuk menjelaskan perasaannya.
Selain itu, sebagian tindakan bunuh diri terjadi secara impulsif, hanya membutuhkan momen singkat pada titik lemah emosional dengan keberadaan sarana yang memudahkan, seperti jembatan tinggi atau lokasi berbahaya lainnya. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah ketidakmampuan mengakses bantuan akibat stigma, di mana banyak orang dengan pikiran bunuh diri tidak tahu harus mencari pertolongan ke mana atau merasa malu untuk membuka diri.
Kalau dibandingkan dengan fenomena hikikomori di Jepang yang menjadi salah satu negara dengan kasus bunuh diri yang tinggi di dunia, sama-sama merefleksikan pergulatan batin individu yang tidak terlihat oleh lingkungan sekitar. Keduanya memperlihatkan bagaimana penderitaan psikologis dapat tersembunyi di balik keseharian yang tampak biasa.
Seorang hikikomori bisa berdiam diri di kamar selama bertahun-tahun tanpa konflik terbuka dengan keluarga, sementara seorang pemuda Bali yang sehari sebelumnya masih bercanda dengan ibunya ternyata menyimpan kesedihan mendalam yang berakhir pada keputusan ekstrem.
Dari sisi psikologis, keduanya terkait dengan distress internal dan perasaan terjebak. Namun, ada perbedaan konteks sosial-budaya yang signifikan. Di Jepang, hikikomori dipengaruhi oleh tekanan akademik, kompetisi kerja, budaya malu, serta ketersediaan ruang privat yang memungkinkan individu menarik diri secara total.
Sementara di Bali, tekanan bisa bersumber dari faktor ekonomi, stigma sosial, dan konstruksi kultural tentang ulah pati yang membuat keluarga enggan membicarakan isu kesehatan mental secara terbuka. Dalam kedua konteks, stigma menjadi penghalang utama akses terhadap pertolongan, tetapi bentuknya berbeda: di Jepang, rasa malu mendorong individu menyembunyikan diri, sedangkan di Bali, rasa malu kolektif membuat keluarga sering menutup rapat masalah. Kesamaan lain adalah adanya akses sarana yang memperbesar risiko.
Antara stigma, spiritualitas, dan rasa malu
Budaya Bali memiliki kekuatan luar biasa dalam membangun kebersamaan, spiritualitas, dan makna hidup. Namun, dalam kasus bunuh diri, muncul paradoks yang penting untuk disoroti. Dalam tradisi Hindu Bali, bunuh diri dipandang sebagai tindakan ulah pati yang membawa konsekuensi spiritual berat, bukan hanya bagi pelaku tetapi juga keluarganya.
Pandangan ini menumbuhkan stigma yang kuat, membuat keluarga sering kali merasa malu, menutup diri, dan enggan mencari bantuan. Walaupun ajaran Hindu melalui prinsip Tri Hita Karana menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam, kenyataannya individu tetap bisa kehilangan makna hidup dan merasa terputus dari nilai spiritual ketika berada dalam krisis.
Tragedi bunuh diri kemudian tidak hanya dilihat sebagai luka personal, melainkan juga sebagai aib kolektif yang menimpa keluarga dan komunitas banjar. Akibatnya, upaya mencari pertolongan sering terhambat karena adanya rasa takut menjadi bahan pembicaraan atau penilaian negatif masyarakat.
Jika ditinjau dari perspektif psiko-sosial, bunuh diri bukan sekadar tindakan individual, melainkan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh ikatan dan integrasi dalam masyarakat. Ada beberapa tipe bunuh diri, dan dalam konteks Bali, setidaknya dua bentuk bisa menjadi relevan.
Pertama, egoistic suicide, yang muncul ketika ikatan sosial seseorang dengan komunitas melemah, membuat individu merasa sendirian dan kehilangan dukungan, meskipun secara budaya Bali menekankan kebersamaan. Kedua, fatalistic suicide, yang dapat terjadi ketika individu merasa terjebak dalam aturan atau tekanan sosial yang terlalu kaku, sehingga tidak melihat jalan keluar lain.
Dalam kasus bunuh diri di Bali, kombinasi antara stigma budaya, tekanan sosial, dan hilangnya keterhubungan spiritual dapat menciptakan kondisi di mana seseorang merasa tidak lagi memiliki ruang untuk berbagi, meminta pertolongan, atau mencari makna.
Selain itu keterasingan sosial diproses layaknya rasa sakit fisik, sehingga stigma, rasa malu, atau kehilangan dukungan komunitas dapat melukai jiwa secara nyata. Kehilangan makna hidup adalah inti dari keputusasaan eksistensial, sementara keberadaan tujuan hidup dan keterhubungan dengan nilai transendental mampu melindungi seseorang dari keinginan untuk mengakhiri hidup. Namun, spiritualitas tidak selalu menjadi pelindung bila makna personal terputus dari ritual komunal.
Kekuatan keluarga untuk melanjutkan perjalanan
Setiap kali terjadi bunuh diri, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu yang pergi, tetapi juga keluarga dan orang-orang terdekat yang ditinggalkan. Mereka yang ditinggalkan kerap mengalami trauma berkepanjangan, rasa bersalah, stigma, hingga kerentanan terhadap depresi bahkan keinginan bunuh diri.
Dalam hal ini, ikatan emosional mendalam antara anak dan figur signifikan, seperti orang tua atau pengasuh, yang memberi rasa aman, kasih sayang, dan kontinuitas memiliki peran penting. Ikatan ini tidak hilang ketika seseorang dewasa, melainkan tetap menjadi dasar dalam menghadapi stres maupun kehilangan. Ketika bunuh diri terjadi, keluarga sering merasakan hancurnya sebuah ikatan secara mendadak yang melahirkan rasa hampa, keterkejutan, kemarahan, dan sering kali perasaan gagal melindungi orang yang dicintai.
Keluarga dengan pola insecure attachment lebih rentan mengalami prolonged grief disorder, depresi, dan kecemasan. Untuk itu, penguatan attachment menjadi hal yang penting, baik antara orang tua dan anak, antarsaudara, pasangan, maupun dalam lingkup komunitas.
Dukungan komunitas seperti banjar dan keluarga besar juga bisa menjadi jaringan attachment eksternal yang memberi rasa memiliki, selama stigma tidak menghalangi. Ritual kolektif, doa bersama, dan forum berbagi pengalaman dapat menolong keluarga agar tidak merasa sendirian.
Selain itu, spiritual attachment yakni keterhubungan dengan nilai spiritual atau keyakinan religius sebagai bentuk secure base baru memiliki peran yang penting. Bagi banyak keluarga Bali, hubungan dengan Sang Hyang Widhi, leluhur, dan komunitas adat dapat menjadi sumber kekuatan yang menopang proses berduka sehingga keluarga korban bunuh diri tidak terperangkap dalam luka berkepanjangan.
Imbauan untuk pemerintah dan masyarakat
Kasus bunuh diri di Jembatan Tukad Bangkung kembali mengingatkan kita bahwa kesehatan mental adalah isu mendesak yang membutuhkan perhatian serius. Dari sudut pandang psikologis, sosial, dan kultural, jelas bahwa bunuh diri adalah hasil dari kompleksitas faktor internal maupun eksternal.
Karena itu, langkah pencegahan harus dilakukan secara komprehensif. Pemerintah perlu mengambil peran aktif dengan menutup atau mengamankan lokasi-lokasi berisiko tinggi seperti jembatan dan tebing. Selain itu, pembangunan layanan krisis 24 jam, hotline darurat, dan pusat konseling di setiap kabupaten menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat memiliki akses cepat pada pertolongan.
Belajar dari negara-negara maju dan wilayah dengan angka bunuh diri tinggi, ada banyak praktik baik yang bisa diadaptasi. Di Jepang, misalnya, selain penyediaan hotline nasional seperti TELL Lifeline dan Inochi no Denwa, pemerintah juga menutup akses ke lokasi-lokasi berbahaya serta memperkuat intervensi berbasis komunitas.
Korea Selatan, yang lama menghadapi tingkat bunuh diri tertinggi, membangun Suicide Prevention Centers yang fokus pada deteksi dini, konseling, dan kampanye publik melawan stigma. Di Eropa Barat, negara seperti Inggris dan Jerman menekankan program gatekeeper training, yakni melatih guru, aparat desa, hingga pemuka agama untuk mengenali tanda krisis dan memberikan pertolongan pertama psikologis.
Sementara di Amerika Serikat, peluncuran hotline nasional di nomor 988 pada tahun 2022 menjadi tonggak penting karena mempermudah akses masyarakat ke layanan krisis secara cepat dan terstandar. Pencegahan bunuh diri membutuhkan kombinasi kebijakan struktural, akses layanan yang mudah, edukasi publik, serta keterlibatan aktif komunitas.
Dengan menyesuaikan praktik-praktik tersebut pada konteks budaya Bali, diharapkan tidak ada lagi jiwa yang hilang dalam sunyi, dan kesehatan mental benar-benar menjadi pilar penting dalam kehidupan masyarakat. (Oleh: Prof Dr dr Cokorda Bagus Jaya Lesmana, SpKJ(K), MARS)
Editor: Redaksi
Reporter: bbn/tim
Berita Terpopuler
6.532 Warga Turun ke Jalan, Tabanan Gelar Grebeg Sampah Serentak
Dibaca: 5739 Kali
Pelajar Tabanan Raih Prestasi Nasional FLS2N 2025, Bupati Sanjaya Bangga
Dibaca: 4845 Kali
Turis Somalia Ngamuk Tuduh Sopir Curi HP, Ternyata Terselip di Jok Mobil
Dibaca: 4284 Kali
Gudang BRI Ubud Ambruk Akibat Longsor
Dibaca: 4123 Kali
ABOUT BALI

Film Dokumenter Hidupkan Kembali Sejarah Tari Kecak di Bedulu

Makna Tumpek Landep Menurut Lontar Sundarigama

Tari Sanghyang Dedari Nusa Penida Diajukan Jadi Warisan Budaya Tak Benda

Mengenal Tetebasan Gering, Topik Menarik di Festival Lontar Karangasem